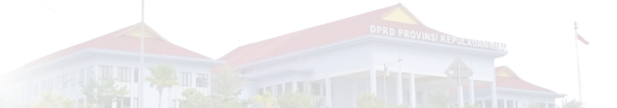Oleh Dr. Kuncoro Hadi, RIFA
Ketua Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah
Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri DPP PKS
Redenominasi Rupiah adalah kebijakan moneter yang memiliki tujuan yang tampak sangat sederhana disebabkab menghilangkan tiga angka nol di belakang nominal mata uang, mengubah Rp1.000 menjadi Rp1. Ironisnya, di balik tujuan menyederhanakan dan menciptakan “elegansi angka” tersebut, tersembunyi sebuah operasi rekayasa sistemik terkompleks yang pernah direncanakan dalam sejarah keuangan modern Indonesia. Kebijakan ini menuntut re-engineering total pada inti operasional sistem finansial nasional, mulai dari Core Banking System hingga setiap mesin kasir di pelosok negeri. Penyederhanaan nominal yang diimpikan sebagai solusi efisiensi jangka panjang, secara paradoks, justru memicu lonjakan biaya implementasi dan risiko psikologis-makro yang harus dimitigasi dengan ketelitian luar biasa.
Kebijakan penyederhanaan digit ini, ditegaskan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025, ditargetkan rampung kerangka Rancangan Undang-Undangnya (RUU) pada 2027. Redenominasi secara fundamental berbeda dari sanering (pemotongan nilai riil mata uang), sebab kebijakan ini tidak mengubah daya beli masyarakat. Manfaat jangka panjangnya adalah kemenangan strategis. Pertama, ia menyederhanakan transaksi akuntansi, mempermudah input data, dan meminimalisasi human error dalam sistem keuangan. Kedua, redenominasi adalah upaya untuk mendongkrak martabat Rupiah, menghilangkan stigma sebagai salah satu mata uang dengan pecahan terbesar di dunia, dan memperkuat kredibilitasnya di mata investor global.
Ancaman Inflasi dan Kritik Kritis terhadap Mitigasi Harga
Namun, keberhasilan visi jangka panjang tersebut terhalang oleh satu risiko sistemik yang paling volatile disebabkan inflasi yang dipicu oleh pembulatan harga (rounding bias). Ini adalah titik kritis yang sering menjadi sumber kegagalan redenominasi di banyak negara. Risiko ini terjadi ketika pedagang dan pelaku usaha, demi kemudahan, secara sewenang-wenang membulatkan harga barang dan jasa ke atas. Contoh klasiknya adalah produk berharga Rp1.100 yang dikonversi menjadi Rp1,10, lalu dibulatkan menjadi Rp2,00 adalah kenaikan harga riil yang substansial. Jika fenomena pembulatan ke atas ini terjadi secara masif di seluruh rantai ritel dan berulang kali, akumulasi kenaikan harga tersebut akan menghasilkan lonjakan inflasi yang tajam (inflation spike). Kritik tajam harus diarahkan pada aspek ini disebabkan tanpa regulasi dan pengawasan harga yang sangat ketat dan transparan, masyarakat akan menyimpulkan bahwa redenominasi hanyalah sanering terselubung, yang pada akhirnya menghancurkan kepercayaan publik dan menghilangkan seluruh manfaat ekonomi yang dijanjikan.
Sementara risiko makro mengancam daya beli, beban implementasi operasional terberat ditanggung oleh sektor perbankan. Redenominasi memerlukan biaya yang sangat tinggi untuk mencetak uang fisik baru dan, yang jauh lebih krusial, untuk melakukan penyesuaian total pada sistem Teknologi Informasi (TI). Setiap bank wajib memodifikasi dan menguji ulang Core Banking System (CBS) mereka agar mampu menangani nilai nominal baru, sekaligus memastikan validitas data historis nasabah, pinjaman, dan aset. Kegagalan sinkronisasi atau downtime sistemik pada hari konversi dapat memicu risiko likuiditas di seluruh jaringan sistem pembayaran nasional (RTGS dan SKNBI). Tantangan ini diperparah oleh tekanan waktu disebabkan meskipun rencana legislasi ditargetkan 2027, Bank Indonesia (BI) sebelumnya menyatakan bahwa persiapan teknis yang komprehensif idealnya membutuhkan waktu hingga 10 tahun.
Menciptakan Strategi Transisi Berjenjang yang Inovatif
Di tengah dilema waktu dan biaya ini, otoritas moneter dan perbankan harus mengevaluasi ulang strategi transisi mereka dan menciptakan pendekatan yang inovatif. Keuntungan digitalisasi Indonesia adalah aset terbesar dalam redenominasi. Indonesia memiliki penetrasi sistem pembayaran digital (seperti QRIS dan mobile banking) yang sangat tinggi, jauh melampaui kondisi ketika rencana ini pertama kali muncul. Infrastruktur digital jauh lebih mudah dan cepat diprogram ulang dibandingkan infrastruktur tunai fisik. Indonesia harus merancang transisi digital-first, mengadopsi model yang berhasil di Turki yaitu menggunakan periode koeksistensi yang jelas dan panjang (minimal 3-5 tahun) yang didahului oleh fase pra-konversi di mana sistem digital diujicobakan. Dengan menjadikan aset digital sebagai shock absorber utama, tekanan pada penyesuaian infrastruktur fisik (ATM/EDC) dapat dikelola secara bertahap, memberikan waktu yang cukup bagi adaptasi publik dan industri.
Prasyarat utama keberhasilan kebijakan ini adalah stabilitas. Kajian historis 32 negara menunjukkan bahwa redenominasi hanya sukses jika diterapkan di tengah kondisi inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang stabil atau tinggi. Jika tidak, kebijakan ini hanya akan memperburuk kondisi. Komitmen politik yang kuat dari pemerintah saat ini adalah modal awal, namun eksekusi harus sangat hati-hati dan berbasis data, tidak hanya ambisi politik semata.
Tiga Pilar Kunci Sukses Redenominasi
Redenominasi 2027 adalah maraton teknis, bukan sprint politik. Untuk mencapai keberhasilan dan memitigasi biaya sistemik yang mengancam, Indonesia memerlukan terobosan solusi konstruktif yang terbagi dalam tiga pilar:
- Mandat Uji Konversi Industri (I-WCT). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BI harus segera mewajibkan Industry-Wide Conversion Testing (I-WCT) terpusat bagi seluruh bank komersial dan sistem pembayaran. Pengujian end-to-end yang ketat ini harus mensimulasikan kegagalan sistem dan interkoneksi, jauh sebelum RUU disahkan, memastikan kesiapan teknis perbankan mencapai 100%.
- Regulasi Anti-Pembulatan Harga Proaktif. Pemerintah wajib segera menetapkan undang-undang atau peraturan yang secara eksplisit mengatur tata cara pembulatan harga dan memberikan sanksi yang sangat tegas bagi praktik rounding-up bias yang berlebihan. Ini adalah pertahanan pertama untuk memenangkan perang psikologis melawan ekspektasi inflasi.
- Literasi Keuangan Berbasis Digital-First. Kampanye sosialisasi harus diintensifkan, secara tegas membedakan redenominasi dari sanering, dan memanfaatkan platform digital untuk menunjukkan secara visual dan real-time bagaimana konversi nominal bekerja. Hanya dengan kesiapan teknis yang tak tercela dan kepercayaan publik yang solid, Indonesia dapat mengubah biaya implementasi yang mahal menjadi fondasi bagi efisiensi ekonomi yang berkelanjutan.
SumberL pks.id